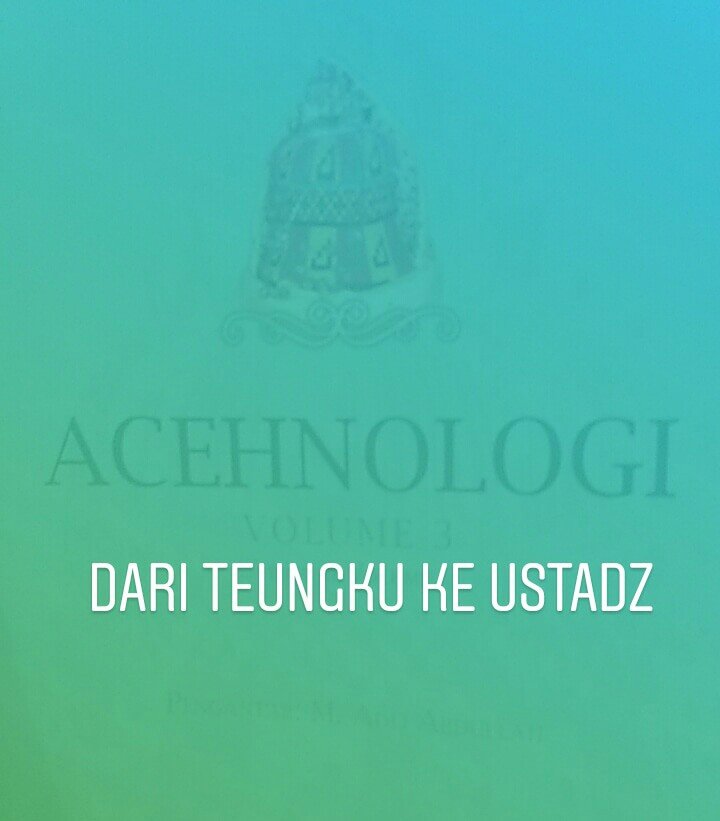
Assalamu'alaikum sahabat ssteemians..
Sebelumnya kita telah membahas tentang peran ustadz sebagai salah satu fenomena yang muncul akhir-akhir ini yang mampu menggeser posisi kelompok dayah termasuk Teungku. Nah dalam dalam bab ini akan di kupas keadaan sosio-kultural pendidikan Islam di Aceh, khususnya mengenai perubahan otoritas religi dalam masyarakat Aceh dari teungku yang merupakan kelompok ulama lokal dan guru si kampung atau di dayah menjadi ustadz yang tidak hanya memainkan peran sebagai guru di pondok pesantren, tetapi juga sebagai guru dakwah. Penyebutan ustadz telah diterima sebagai 'gelar' dalam bidang keagamaan di Aceh sejak tahun 1980-an, masa dimana telah dikenal beberapa pondok pesantren modern.
Di Aceh, panggilan teungku biasa diemban oleh para ulama. Demikian pula dikenal sebutan abu, abi, waled, abati, dan abon. Dalam hirarkinya, ulama yang paling tinggi dikenal dengan abu, yang terkadang kerap diikuti dengan kampung kediaman mereka, seperti Abu Tanoh Mirah, Abu Kuta Krueng, dan lain sebagainya. Panggilan abu juga terkadang dihubungkan dengan Teungku Chik atau Abu Chik yang biasanya menjadi kepala dayah. Posisi dan sistem ini kiranya sama dengan pesantren yang ada di Jawa. Peran Teungku Chik sepadan dengan posisi Kyai di pesantren. Peran Abu Chik ini tidak hanya di dayah, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual bagi masyarakat, sebagai mediator perdamaian, dan Syeikh apabila ia memiliki tarekat.
Adapun Teungku menduduki posisi di bawah Abu Chik yang secara akademik memiliki peran yang sama dengan ustadz di dayah modern ini.pembagian teungku pun ada beberapa macam yaitu seperti Teungku Bale yang mengajar oada tingkat SMU, Teungku Rangkang yang bertindak sebagai asisten Teungku Bale dan menduduki tingkat SMP, dan yang terakhir yaitu Teungku Meunasah, tugas mereka bukanlah di dayah melainkan di gampong atau kampung, mereka adalah pengajar ilmu-ilmu dasar keislaman bagi anak-anak sebelum mereka belajar di dayah atau sekolah umum. Selain itu adapula penyebutan seseorang sebagai teungku bukan karena ilmu agama serta karisma yang dimilikinya, melainkan hanya karena persoalan ideologi semata. Seperti panggilan Teungku Chik di Tiro, Teungku Abdullah Syafi'i, dan Teungku Muzakkir Manaf, dan Abu Beureueh.
Seiring waktu berjalan peran Teungku kini telah jarang dijumpai, karena posisinya telah tergantikan dengan ustadz. Dalam studi ini, dapat dilihat bahwa ada konflik antara kelompok Teungku dengan ustadz du salah satu kawasan di Aceh. Ada yang. Mengatakan bahwa kedatangan ustadz telah menantang otiritas dan karisma pada teungku. Hal ini dapat dilihat dari kelompok masyarakat Aceh yang lebih memilih dan tertarik untuk memasukkan anak mereka ke pondok pesantren modern ketimbang ke dayah. Agaknya peran ustadz kini memiliki arti penting bagi masyarakat setempat, terlepas dari bagaimanakah pondok pesantren khususnya ustadz atau guru (yang memiliki misi tertentu) mempengaruhi anak mereka. Yang jelas dalam kondisi ini peran dayah semakin menurun dalam pengembangan pendidikan, selain kurangnya keterlibatan ulama dalam politik Aceh, juga tidak ada jaminan masa depan bagi lulusan dayah. Situasi ini tentunya berbeda dengan mereka yang mondok di pesantren modern, karena kemungkinan mereka untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi sangat besar. Acehnologi berusaha memberikan gambaran tentang pengaruh guru yang seharusnya diseleksi terlebih dahulu.