
Adaptasi dari karya sastra seperti novel ke dalam karya audio visual (film) sekarang semakin banyak. Banyak alasan yang membuat pekerja film mencoba mengadaptasikan karya sastra ke dalam bentuk film. Salah satunya saya rasa, produser film sangat mempertimbangkan basis penonton. Jumlah penonton akan dengan mudah diprediksi dari jumlah buku yang laku di pasaran. Ini memang hitunga kasar, ditambah lagi dengan penonton non-pembaca yang penasaran dengan cerita novel namun mereka terlalu malas untuk membaca. Maka filmnya akan menjadi pilihan.
Untuk mendukung pendapat saya di atas, lihat saja novel apa yang difilmkan. Rata-rata adalah novel best-seller yang mempunyai jumlah pembaca sangat banyak. Prediksi asal-asalannya, nanti film yang telah berhasil di angkat dari cerita karya sastra novel akan mendapat penonton yang berasal dari pembaca. Jadi semakin novel tersebut best-seller, kemungkinan mendapat penonton yang banyak juga akan sangat mungkin. Namun, bukannya tidak mempunyai kendala. Sebagian pembaca yang merupakan penggemar berat (fanboy) kadang sangat kecewa dengan film yang diangkat dari novel favoritnya.
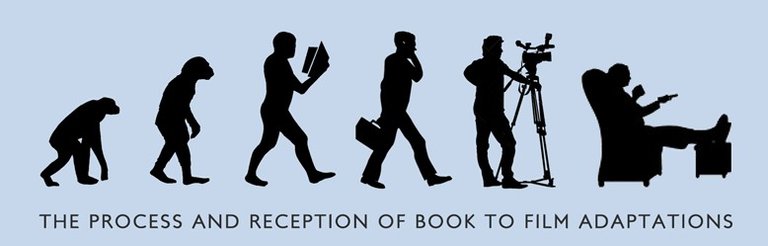
Mereka kecewa dengan beberepa bagian novel yang dihilangkan atau ditambahkan setelah diadaptasi menjadi film. Kemudian, imajinasi sutradara sepertinya berbeda dengan apa yang mungkin bisa dia tangkap dari novel tersebut. Maka sangat mungkin beberapa film yang diadaptasi dari novel mendapat kritik yang lebih. Di Indonesia, trend produksi film adaptasi sedang maraknya. Terakhir, berita film yang akan diangkat dari salah satu karya sastra fenomenal karya Pramoedya, Bumi Manusia juga menuai kritik. Padahal film belum juga dikerjakan.
Ada beberapa hal yang seharusnya kita ketahui terkait adaptasi novel ke film. Novel yang merupakan karya sastra tidak mutlak memiliki hard fact (fakta historis yang valid). Bagaimanapun, ia telah dibumbui oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Jadi, hanya ada mental fact, fakta historis yang telah mengalami perubahan oleh imajinasi pengarang. Maka ketika menjadi film, yang notabene adalah karya yang lebih kompleks, perubahan mungkin tidak akan terjadi. Apalagi idealisme sutradara sangat dominan di sana, belum lagi kepentingan produser.
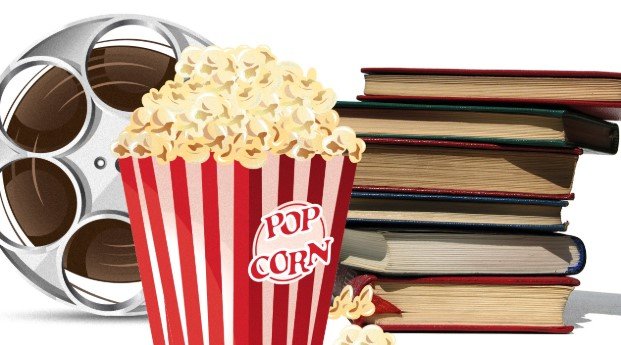
Penghilangan beberapa adegan dalam film yang diadaptasi dari novel bukan karena alasan. Medium sinema lebih kompleks dari karya sastra. Bayangkan kamu harus menjabarkan sebuah adegan dengan segala realita dari sebuah tulisan, itu tidak mudah. Kemudian durasi waktu yang kamu peroleh hanya dua jam (standar), bagaimana kamu menceritakan semuanya? Kemudian, film harus mengalami proses sensor yang ketat. Saya tidak paham bagaimana sebuah karya sastra ketika mengalami proses sensor, mungkin kawan-kawan bisa membagikan informasinya. Tapi George Bluestone, dalam bukunya Novels into Film menulis:
“novels are relatively free of censorship, but films are not, having to obey certain moral criteria such as the Production Code.” Novel relatif bebas dari censorship, namun film seringkali tidak, karena harus mengikuti kriteria-kriteria moral tertentu seperti yang terpapar pada Kode Produksi.
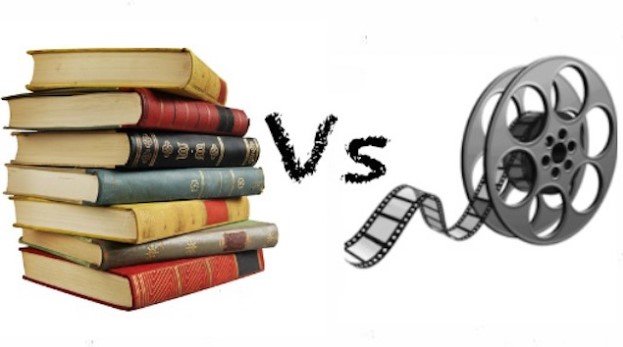
Oleh karena itu, jika kita bijak dan menempatkan diri pada posisi sebagai penikmat karya, maka kita harus menyimpan imajinasi kita terhadap karya sastra novel dan menerima apa yang sudah dikerjakan oleh sutradara. Dua karya yang berbeda medium ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi ketika keduanya berkolaborasi, akan memberikan suatu pengalaman yang berbeda.
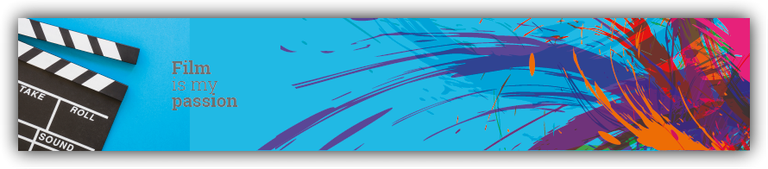
Kiban le abg croeng tat neu puget tulisan.salut salut.mntap bg rafsan.
Beule membaca @afiatmusa hehe
Di tambah pecinta novel terkadang terlanjur fanatik dengan alur cerita yang sudah baku dalam kenangan sistem imajinasinya sendiri ..
Saya pribadi mengapresiasi keduanya..
Karna saya menyukai keduanya baik novel dan film.
-Sebagai pengarang novel tentu bukan hal mudah memindah kan rangkaian ide/imajinasi nya ke lembar kertas dalam bentuk tulisan mengajak orang lain memproduksi alam imajinasinya sendiri.
-sutradara/pembuat film bekerja terbalik dari si pengarang novel.
Memindahkan tulisan dari lembar kertas menjadi karya imajinasi visual.
Tentu membutuhkan imajinasi yang luar biasa untuk keduanya.
Thanks infonya bg @akbarrafs
Luar biasa tambahannya bang @komenk81. Benar, keduanya adalah produk dari imajinasi seniman. Kita bersyukur bebas menikmati keduanya sekarang.
Mungkin persepsi visual yang berbeda. Saya ingat beberapa novel best seller seumpama Lupus di jaman saya maupun ayat ayat cinta walau mencatat penonton dramatis tapi bagi penikmat seni tulisan visualisasi tetap membatasi. Ketika membaca, dengan kemampuan penulis mendeskripsikan keadaan setting image pembaca melayang kemana2, tentu kecewa ketika menonton filmnya tak seperti yang dibayangkan.
Deskripsi yang memakan 5 alinea dalam film hanya tampak 3 detik.
Nah, inilah yang saya bahas di atas. Kita sebagai penikmat karya sastra bisa saja merasa kecewa dengan adaptasi novel ke film. Itulah yang saya coba tulis dari kaca mata saya bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi pembuat film ketika memvisualkan setiap kalimat dan paragraf kepada realitas lain, film. Begitu pula ketika film maker menerjemahkan 5 alinea ke dalam satu gambar hanya memakan 3 detik. Misalnya:
Dalam karya sastra ditulis:
Paragraf di atas tidak mudah dilukiskan dalam medium audio visual (Film). Seorang sutradara akan menanyakan kepada dirinya sendiri:
Dan kita bisa membayangkan hasilnya hanya beberapa detik dari tayangan audio visual
Saya banyak mendengarkan orang-orang yang hobi membaca novel kecewa ketika novel bacaannya dijadikan film. Katanya banyak sekali pengurangan konten atau perubahan alur cerita.
Coba baca dengan seksama tulisan yang saya bahas di atas. Saya mencoba memberi pendapat, kenapa ada pengurangan, perubahan alur cerita, dll
Iya, Bang. Saya pribadi tak masalah karena jarang baca novel. Hehe.
Dua karya berbeda idealnya harus dinilai berbeda pula, tapi di situlah letak tantangannya, mengkaryakan karya lain itu memang tidak mudah, karena publik sudah mendapat persepsi tersendiri.
Done